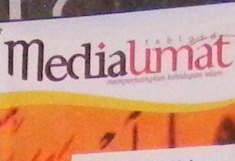Oleh : M. Shiddiq Al-Jawi
Anda mungkin pernah mendengar pernyataan begini. Bahwa Imlek itu hanyalah tradisi dan bukan bagian ajaran agama tertentu. Karenanya umat Islam khususnya yang beretnis Tionghoa boleh-boleh saja merayakan Imlek. Benarkah Imlek hanya tradisi? Apakah boleh muslim turut merayakan Imlek? Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan persoalan ini kepada umat Islam, dengan menelaah ajaran agama Khonhuchu, serta menelaah hukum syariah Islam yang terkait dengan keterlibatan kaum muslimin dalam perayaan hari raya agama lain.
Imlek Bagian Ajaran Agama Khonghucu, Bukan Sekedar Tradisi Tionghoa
Memang tak jarang kita dengar dari orang Tionghoa, termasuk tokoh-tokohnya yang sudah masuk Islam, bahwa Imlek itu sekedar tradisi. Tidak ada hubungannya dengan ajaran suatu agama, sehingga umat Islam boleh turut merayakannya. Sebagai contoh, Sekretaris Umum DPP PITI (Pembina Iman Tauhid Islam), H. Budi Setyagraha (Huan Ren Cong), pernah menyatakan bahwa Imlek adalah tradisi menyambut tahun baru penanggalan Cina, datangnya musim semi, dan musim tanam di daratan Cina. H. Budi Setyagraha berkata,”Imlek bukan perayaan agama.” (Lihat “Sekjen DPP PITI : Rayakan Imlek Jangan Berlebihan”, Kedaulatan Rakyat, Selasa, 13 Pebruari 2007, hal. 2).
Jika kita mendalami agama Khonghucu, khususnya mengenai hari-hari rayanya, akan terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Sebab sebenarnya Imlek adalah bagian integral dari ajaran agama Khonghucu, bukan semata-mata tradisi.
Dalam bukunya Mengenal Hari Raya Konfusiani (Semarang : Effhar & Dahara Prize, 2003) hal. vi-vii, Hendrik Agus Winarso menyebutkan bahwa masyarakat kurang memahami Hari Raya Konfusiani. Kata beliau mencontohkan,”Misalnya Tahun Baru Imlek dianggap sebagai tradisi orang Tionghoa.” Dengan demikian, pandangan bahwa Imlek adalah sekedar tradisi, yang tidak ada hubungannya dengan agama, menurut penulis buku tersebut, adalah suatu kesalahpahaman (Ibid., hal. v).
Dalam buku yang diberi kata sambutan oleh Ketua MATAKIN tahun 2000 Hs. Tjhie Tjay Ing itu, pada hal. 58-62, Hendrik Agus Winarso telah membuktikan dengan meyakinkan bahwa Imlek adalah bagian ajaran Khonghucu. Hendrik Agus Winarso menerangkan, Tahun Baru Imlek atau disebut juga Sin Cia, merupakan momentum untuk memperbarui diri. Momentum ini, kata beliau, diisyaratkan dalam salah satu kitab suci Khonghucu, yaitu Kitab Lee Ki, bagian Gwat Ling, yang berbunyi :
“Hari permulaan tahun (Liep Chun) jadikanlah sebagai Hari Agung untuk bersembahyang besar ke hadirat Thian, karena Maha Besar Kebajikan Thian. Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia… (Tiong Yong XV : 1-5).
(Lihat Hendrik Agus Winarso, Mengenal Hari Raya Konfusiani, [Semarang : Effhar & Dahara Prize, 2003], hal. 60-61).
Penulis buku tersebut lalu menyimpulkan Imlek adalah bagian ajaran Khonghucu. Beliau mengatakan :
“Dengan demikian, menyambut Tahun Baru bagi umat Khonghucu Indonesia mengandung arti ketakwaan dan keimanan.” (ibid.,hal. 61).
Maka tidaklah benar pendapat yang menyebutkan bahwa Imlek hanya sekedar tradisi orang Tionghoa, atau Imlek bukan perayaan agama. Yang benar, Imlek justru adalah bagian ajaran agama Khonghucu, bukan sekedar tradisi.
Lagi pula, harus kami tambahkan bahwa boleh tidaknya seorang muslim melakukan sesuatu, tidaklah dilihat apakah sesuatu itu berasal dari tradisi atau ataukah dari agama. Seakan-akan kalau berasal dari tradisi hukumnya boleh-boleh saja dilakukan, sementara kalau dari agama lain hukumnya tidak boleh.
Standar semacam itu sungguh batil dan tidak ada dalam Islam. Karena standar yang benar menurut Islam, adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman :
“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya.” (QS Al-A’raaf [7] : 3)
Kalimat “maa unzila ilaykum min rabbikum” dalam ayat di atas yang berarti “apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”, artinya adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. (Tafsir Al-Baidhawi, [Beirut : Dar Shaadir], Juz III/2).
Jadi suatu perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan, tolok ukurnya adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Apa saja yang benar menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah, berarti boleh dikerjakan. Sebaliknya apa saja yang batil menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah, berarti tidak boleh dilakukan.
Maka kalau kita hendak menilai perbuatan muslim turut merayakan Imlek menurut Islam, tolok ukurnya harus benar. Yaitu harus kita lihat adalah apakah perbuatan itu boleh atau tidak menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah, bukan melihat apakah Imlek itu dari tradisi atau dari agama.
Sungguh kalau seorang muslim menggunakan tolok ukur tadi, yaitu melihat sesuatu itu dari tradisi atau agama, ia akan tersesat. Sebab suatu tradisi tidak selalu benar, adakalanya ia bertentangan dengan Islam dan adakalanya sesuai dengan Islam. Contoh, free sex pada masyarakat Barat yang Kristen. Free sex jelas telah menjadi tradisi Barat, meski perbuatan kotor itu bukan bagian agama Kristen/Katholik, karena agama ini pun mengharamkan zina. Lalu, apakah karena free sex itu sekedar tradisi, dan bukan agama, lalu umat Islam boleh melakukannya? Jelas tetap tidak boleh, bukan?
Walhasil, mari kita gunakan barometer yang benar untuk menilai suatu perbuatan. Barometernya, bukan dilihat dari segi asalnya apakah suatu perbuatan itu dari tradisi atau agama, melainkan dilihat dari segi boleh tidaknya perbuatan itu menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah. Inilah pandangan yang haq, tidak ada yang lain.
Haram Atas Muslim Turut Merayakan Imlek
Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah, haram hukumnya seorang muslim turut merayakan hari raya agama lain, termasuk Imlek, baik dengan mengikuti ritual agamanya maupun tidak, termasuk juga memberi ucapan selamat Gong Xi Fat Chai. Semuanya haram.
Imam Suyuthi berkata,”Juga termasuk perbuatan mungkar, yaitu turut serta merayakan hari raya orang Yahudi, hari raya orang-orang kafir, hari raya selain orang Arab [yang tidak Islami], ataupun hari raya orang-orang Arab yang tersesat. Orang muslim tidak boleh melakukan perbuatan itu, sebab hal itu akan membawa mereka ke jurang kemungkaran…” (Imam Suyuthi, Al-Amru bi Al-Ittiba’ wa An-Nahyu ‘An Al-Ibtida` (terj.), hal. 91).
Khusus mengenai memberi ucapan selamat, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata,”Adapun memberi ucapan selamat yang terkait syiar-syiar kekufuran yang menjadi ciri khas kaum kafir, hukumnya haram menurut kesepakatan ulama, misalnya memberi selamat atas hari raya atau puasa mereka...” (Ahkam Ahli Adz-Dzimmah, [Beirut : Darul Kutub Al-'Ilmiyah], 1995, Juz I/162).
Dalil Al-Qur`an yang mengharamkan perbuatan muslim merayakan hari raya agama kafir di antaranya firman Allah SWT :
“Dan (hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah) orang-orang yang tidak menghadiri kebohongan…” (QS Al-Furqan [25] : 72).
Kalimat “laa yasyhaduuna az-zuur” dalam ayat tersebut menurut Imam Ibnu Taimiyah maknanya yang tepat adalah tidak menghadiri kebohongan (az-zuur), bukan memberikan kesaksian palsu. Dalam bahasa Arab, memberi kesaksian palsu diungkapkan dengan kalimat yasyhaduuna bi az-zuur. Jadi ada tambahan huruf jar yang dibaca bi. Bukan diungkapkan dengan kalimat yasyhaduuna az-zuur (tanpa huruf jar bi). Maka ayat di atas yang berbunyi “laa yasyhaduuna az-zuur” artinya yang lebih tepat adalah ” tidak menghadiri kebohongan”, bukannya ” memberikan kesaksian palsu.” (M. Bin Ali Adh-Dhabi’i, Mukhtarat min Kitab Iqtidha` Shirathal Mustaqim Mukhalafati Ash-habil Jahim (terj.), hal. 59-60)
Sedang kata “az-zuur” (kebohongan) itu sendiri oleh sebagian tabi’in seperti Mujahid, adh-Dhahak, Rabi’ bin Anas, dan Ikrimah artinya adalah hari-hari besar kaum musyrik atau kaum jahiliyah sebelum Islam (Imam Suyuthi, Al-Amru bi Al-Ittiba’ wa An-Nahyu ‘An Al-Ibtida` (terj.), hal. 91-95).
Jadi, ayat di atas adalah dalil haramnya seorang muslim untuk merayakan hari-hari raya agama lain, seperti hari Natal, Waisak, Paskah, Imlek, dan sebagainya.
Imam Suyuthi berdalil dengan dua ayat lain sebagai dasar pengharaman muslim turut merayakan hari raya agama lain (Lihat Imam Suyuthi, ibid., hal. 92). Salah satunya adalah ayat :
“Dan sesungguhnya jika kamu [Muhammad] mengikuti keinginan mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.” (QS Al-Baqarah [2] : 145).
Menurut Imam Suyuthi, larangan pada ayat di atas tidak hanya khusus kepada Nabi SAW, tapi juga mencakup umat Islam secara umum. Larangan tersebut adalah larangan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh atau orang kafir [seperti turut merayakan hari raya mereka]. Sedangkan yang mereka lakukan bukanlah perbuatan yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya (Lihat Imam Suyuthi, ibid., hal. 92).
Adapun dalil As-Sunnah, antara lain Hadits Nabi SAW,“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka.” (HR Abu Dawud).
Dalam hadits ini Islam telah mengharamkan muslim untuk menyerupakan dirinya dengan kaum kafir pada hal-hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka, seperti hari-hari raya mereka. Maka dari itu, haram hukumnya seorang muslim turut merayakan hari-hari raya agama lain (Lihat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Penjelasan Tuntas Hukum Seputar Perayaan, [Solo : Pustaka Al-Ummat], 2006, hal. 76).
Berdasarkan dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah di atas, haram hukumnya seorang muslim turut merayakan Imlek dalam segala bentuk dan manifestasinya. Haram bagi muslim ikut-ikutan mengucapkan Gong Xi Fat Chai kepada orang Tionghoa, sebagaimana haram bagi muslim menghiasi rumah atau kantornya dengan lampion khas Cina, atau hiasan naga dan berbagai asesoris lainnya yang serba berwarna merah. Haram pula baginya mengadakan berbagai macam pertunjukan untuk merayakan Imlek, seperti live band, karaoke mandarin, demo masak, dan sebagainya.
Semua bentuk perbuatan tersebut haram dilakukan oleh muslim, karena termasuk perbuatan merayakan hari raya agama kafir yang telah diharamkan Al-Qur`an dan As-Sunnah.
Himbauan Kepada Muslim Etnis Tionghoa
Terakhir, kami sampaikan seruan dan himbauan kepada saudara-saudaraku muallaf dari etnis Tionghoa, hendaklah Anda masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhannya (kaffah). Janganlah Anda -semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda semua- mengikuti langkah-langkah setan, yakni masuk ke dalam agama Islam namun masih mempertahankan sebagian ajaran lama yang dulu Anda peluk dan Anda amalkan, seperti perayaan Imlek. Marilah kita renungkan firman Allah SWT :
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah [2] : 208)
Wallahu a’lam bi al-shawab.